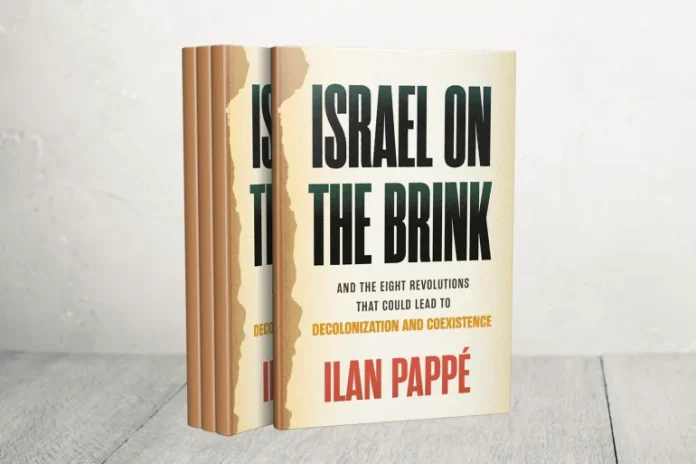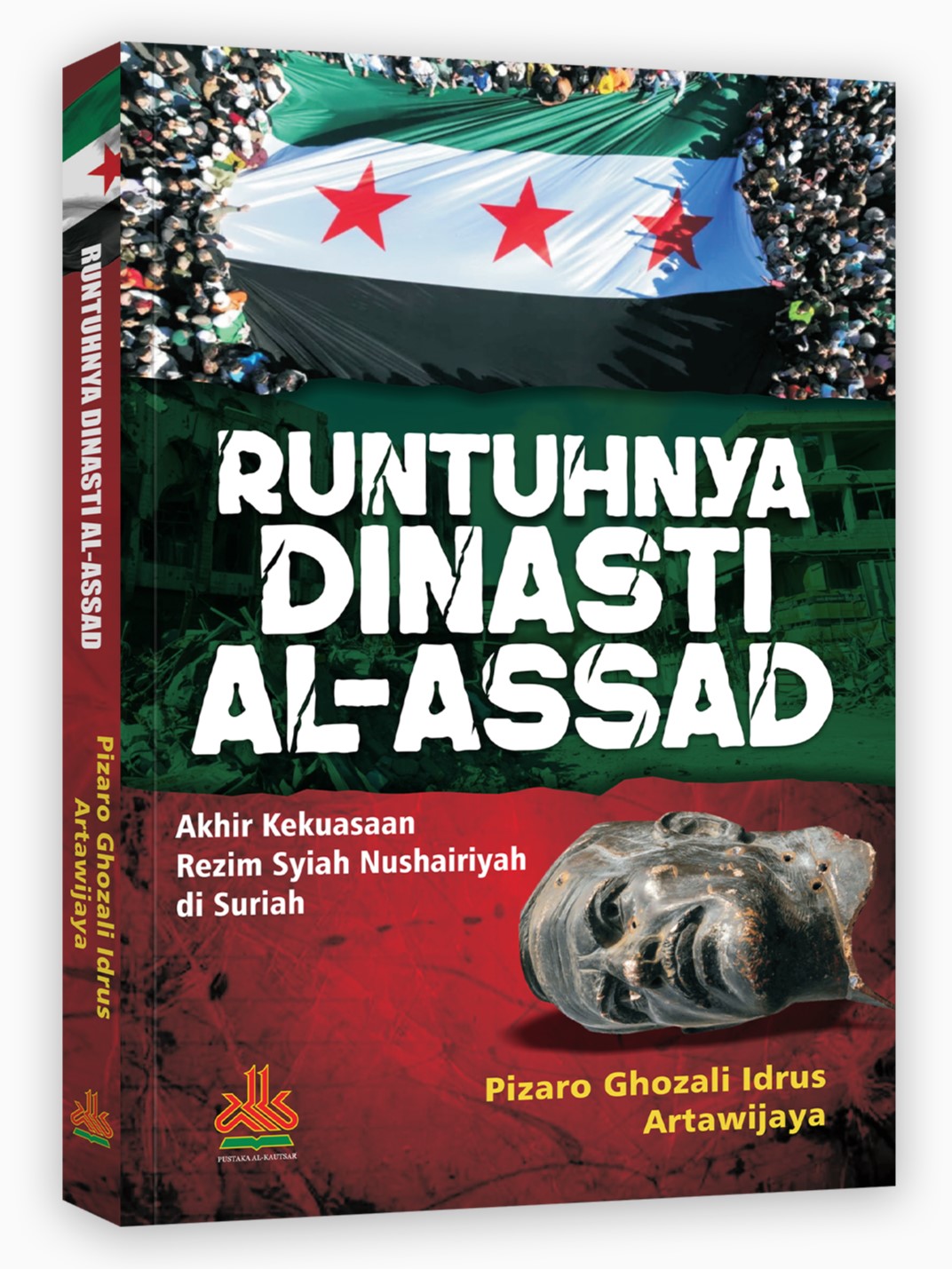Pada September 2025, sejarawan dan profesor asal Israel Ilan Pappé menerbitkan buku berjudul Israel on the Brink: Eight Revolutionary Shifts That Could Lead to Decolonisation and Coexistence (Israel di Ambang Keruntuhan: Delapan Revolusi yang Dapat Mengarah pada Dekolonisasi dan Koeksistensi).
Pappé dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka di kalangan “sejarawan baru” Israel—kelompok akademisi yang menolak tradisi historiografi resmi Zionis dan menjauh dari mitos-mitos pendirian negara, dengan menempatkan Nakba Palestina sebagai pusat pembacaan sejarah yang lebih jujur dan kritis.
Para “sejarawan baru” seperti Tom Segev, Simha Flapan, Adam Raz, Benny Morris, dan Ilan Pappé membantah narasi resmi Israel tentang Perang 1948.
Salah satu di antaranya, Avi Shlaim—sejarawan Yahudi berdarah Irak yang mengajar di Universitas Reading dan Oxford—menyebut Pappé sebagai salah satu peneliti yang paling memahami detail konflik Palestina, latar belakangnya, serta kerumitan dan cabang-cabang persoalannya.
Buku ini terbit serentak dalam dua edisi bahasa Inggris: di Amerika Serikat (AS) melalui Beacon Press, dan di Inggris melalui OneWorld Publications. Tebalnya 216 halaman.
Pappé pernah mengajar sejarah di Universitas Haifa. Saat ini ia menjabat profesor sejarah di Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Internasional, Universitas Exeter, Inggris, sekaligus Direktur Pusat Studi Palestina Eropa di universitas tersebut.
Sejumlah karyanya yang penting antara lain The Ethnic Cleansing of Palestine (Pembersihan Etnis Palestina), Ten Myths About Israel (Sepuluh Mitos tentang Israel), A History of Modern Palestine (Sejarah Palestina Modern), dan A Very Short Introduction to the Israel–Palestine Conflict (Pengantar Singkat Sejarah Konflik Israel–Palestina).
Dalam buku terbarunya ini, Ilan Pappé menilai Israel tengah mengalami perpecahan serius. Ia mengulas sejumlah persoalan mendasar yang, menurutnya, harus dihadapi apabila ingin membuka jalan menuju masa depan yang damai bagi Palestina dan Yahudi.
Israel, kata Pappé, tidak mungkin terus berjalan di jalur yang sama. Peristiwa 7 Oktober 2023, disusul invasi Israel ke Gaza, telah menyingkap retakan mendalam pada fondasi negara itu.
Israel tampil sebagai negara yang gagal melindungi warganya sendiri, terbelah antara kelompok religius “mesianistik” dan kaum “liberal” yang selektif, dibenci oleh lingkungan regionalnya, serta kian kehilangan dukungan komunitas Yahudi dunia.
Pada saat yang sama, para pemimpinnya membenarkan kampanye pengeboman yang melampaui kekejaman terburuk Perang Dunia II, memicu bencana kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza.
Dengan demikian, Israel bergerak menuju status negara paria. Dalam pandangan Pappé, musuh terbesar Israel kini bukan lagi Hamas, melainkan Israel itu sendiri.
Buku ini hadir pada saat yang, menurut Pappé, sangat menentukan. Ia berupaya membuka jalan keluar dari bencana nasionalisme Yahudi dan negara Zionis melalui visi berjangka panjang yang berakar pada keadilan restoratif dan dekolonisasi.
Gagasan itu mencakup hak kembali para pengungsi, pembongkaran permukiman, serta pembangunan jembatan komunikasi dengan dunia Arab. Masa depan, tegas Pappé, dapat berupa rekonsiliasi—bukan perang tanpa akhir.
Pappé berpendapat bahwa sejak terpilihnya pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel pada 2022, disusul serangan “Thaufan Al-Aqsha” pada 7 Oktober 2023, perang Israel di Gaza, dan genosida yang mengikutinya, perpecahan politik laten di dalam negara Yahudi itu melebar secara berbahaya dan berpotensi berujung pada keruntuhan.
Melalui buku ini, Pappé memaparkan gagasan-gagasannya tentang risiko dan peluang yang lahir dari momen sejarah tersebut, dengan tujuan mendorong transisi yang sedamai mungkin.
Ia berargumen bahwa delapan “revolusi kecil” atau “lompatan historis kualitatif” diperlukan untuk membuka masa depan yang lebih menjanjikan. Di antaranya:
- Menempatkan kembali “hak kembali” pengungsi Palestina sebagai inti visi masa depan.
- Merumuskan ulang definisi komunitas Yahudi di Palestina historis.
- Menyelesaikan rancangan masa depan permukiman Yahudi di Tepi Barat pasca-1967.
- Menyusun strategi baru bagi gerakan nasional Palestina yang bersatu dengan mengadopsi opsi negara demokratis tunggal.
Pappé dengan tegas membayangkan masa depan yang lebih adil: sebuah negara demokratis yang telah didekolonisasi, bagi warga Palestina dan Israel secara setara. Ia juga menelusuri jalan-jalan yang memungkinkan untuk mencapainya.
Ulasan ini berupaya menampilkan dan mendiskusikan isu-isu utama dalam buku tersebut. Termasuk skenario kejatuhan yang mungkin terjadi, bangkitnya kanan religius Zionis, potensi pembelahan negara menjadi “Negara Yudea” yang religius dan “Negara Israel” yang sekuler, jalur-jalur disintegrasi, konsep pusat gravitasi dan basis kekuatan, serta kelelahan militer Israel—baik dari sisi sumber daya manusia maupun persenjataan.
Skenario kejatuhan yang mungkin terjadi
Kendati masih mendominasi dan unggul secara militer atas para pesaing regionalnya, entitas Zionis justru berada pada fase paling rapuh dalam sejarahnya. Pertanyaan mendasarnya: apakah proyek negara Yahudi masih dapat dipertahankan?
Terlepas dari kehancuran dan keputusasaan yang ditimbulkan oleh genosida yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza selama dua tahun terakhir, Israel justru berpotensi memasuki periode terlemah dalam sejarah singkatnya.
Dalam buku ini, Pappé menegaskan bahwa jalur yang kini ditempuh Israel—melanjutkan kebijakan lama dengan intensitas yang sama—tidak berkelanjutan. Tekanan domestik, politik, militer, dan internasional akan terus memperdalam ketidakstabilan.
“Kejatuhan Israel yang mungkin terjadi bisa menyerupai berakhirnya negara Vietnam Selatan—yakni penghapusan total sebuah negara—atau seperti Afrika Selatan, yaitu runtuhnya sebuah rezim ideologis tertentu, rezim apartheid, dan digantikan oleh sistem lain. Dalam kasus Israel, saya percaya unsur-unsur dari kedua skenario itu akan terungkap lebih cepat daripada yang dapat kita pahami atau persiapkan,” tulis Pappé.
Menurut Pappé, jalan yang membawa Israel ke titik ini adalah ekstremisme religius yang kian mengeras, yang diwakili oleh figur-figur di puncak kekuasaan seperti Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, dan Bezalel Smotrich.
Lalu, seperti apa masa depan yang menanti mereka—dan rakyat Palestina yang telah lama menderita?
Pappé memandang Israel tengah menuju keruntuhan atau ledakan dari dalam (implode).
Ia mendefinisikan pemerintahan kanan-ekstrem Netanyahu saat ini sebagai “Zionisme baru” (neo-Zionist): suatu fase di mana nilai-nilai Zionisme lama menjelma semakin ekstrem, rasis, supremasis, dan brutal.
Negara Zionis versi baru ini, tulis Pappé, telah meninggalkan pendekatan bertahap dan pembersihan etnis perlahan terhadap Palestina—sebagaimana dipraktikkan oleh pemerintahan Zionis sebelumnya.
“Negara Yehuda” dan “Negara Israel”
Israel menggunakan genosida sebagai senjata untuk mengosongkan Jalur Gaza dari warga Palestina, dan kelak—bahkan dalam waktu dekat—Tepi Barat.
Pemerintahan Israel kini dikuasai kelompok ekstremis Yahudi yang telah mengubah entitas ini menjadi apa yang oleh Ilan Pappé—dengan merujuk pada sejarah perpecahan Kerajaan Bani Israel di masa lalu—disebut sebagai “Negara Yehuda”.
Sebuah negara yang, menurutnya, pada akhirnya akan terpisah dari “Negara Israel”, sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah kuno.
“Negara Yehuda” versi baru ini dijalankan oleh para pemukim Yahudi fanatik. Sekitar 750.000 pemukim tinggal di Tepi Barat, menggabungkan Zionisme religius dengan Yudaisme Ortodoks.
Mereka mengusung visi pendirian sebuah imperium Yahudi yang menguasai negeri-negeri Arab di sekitarnya, terutama Lebanon, Yordania, dan Suriah.
Kebencian yang dianut para pengelola “negara Zionisme baru” ini—Negara Yehuda—tidak hanya diarahkan kepada warga Palestina, tetapi juga menjalar ke kalangan Yahudi Israel yang sekuler.
Kondisi ini, menurut Pappé, akan membawa Israel menuju perpecahan internal yang pada akhirnya membuatnya tidak berkelanjutan sebagai sebuah negara.
Seiring dengan merosotnya kekuatan Amerika Serikat dan menyusutnya imperium globalnya—sebuah proses yang, menurut Pappé, dipercepat oleh ketidakmampuan dan korupsi pemerintahan Presiden AS Donald Trump—pilar utama dukungan bagi Israel juga akan terkikis.
AS, pada gilirannya, akan dipaksa melakukan penghematan dan menarik diri secara bertahap dari Timur Tengah.
Pertanyaannya kemudian: apa arti runtuhnya entitas ini bagi warga Israel, rakyat Palestina, dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan? Apakah ia akan menandai awal dari proses dekolonisasi? Ataukah justru memperdalam spiral kekerasan, pertumpahan darah, dan ekstremisme?
Mungkinkah Israel digantikan oleh sebuah negara sekuler dan demokratis—negara di mana warga Palestina dan Israel memiliki hak yang setara, sebuah negara “satu orang, satu suara” seperti Afrika Selatan pasca-apartheid? Ataukah Israel akan menyusut menjadi negara teokratis yang otoriter, dengan eksodus elite sekuler dan terdidik, serta kehancuran ekonomi akibat perang yang tak berkesudahan?
Agresivitas, ekspansi, dan kolonisasi merupakan “kode genetik” Israel, disertai keyakinan bahwa mereka adalah penguasa Timur Tengah dan kekuatan hegemonik kawasan.
Dari waktu ke waktu, mereka melangkah lebih jauh ke arah yang sama, memperlihatkan kepada negara-negara di sekitarnya bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertindak sesuka hati—tanpa mengindahkan hukum internasional maupun kedaulatan negara lain.
Ada perasaan nyata di kalangan elite Israel bahwa dunia Arab—atau setidaknya rezim-rezim penguasanya—berada sepenuhnya di bawah kendali mereka. Pappé menilai, inilah dua tujuan utama serangan Israel terhadap Doha pada September 2025.
Pertama, tujuan taktis terkait negosiasi; kedua, penegasan arogansi bahwa merekalah kekuatan sejati di kawasan.
Pandangan ini sepenuhnya sejalan dengan visi “mesianistik-redemptif” Zionisme baru, yang bercita-cita membangun kembali Kerajaan Israel kuno sebagaimana diklaim bersumber dari Perjanjian Lama.
Para penganutnya meyakini bahwa kini mereka memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mewujudkan proyek tersebut.
Di Israel, kelompok Yahudi yang diasosiasikan dengan “Negara Yehuda” kerap disebut sebagai Mizrahi.
Ketegangan antara mereka dan kaum Ashkenazi—Yahudi Eropa yang mendirikan negara Zionis dan mendominasinya hingga dekade 1980-an—telah berlangsung lama. Keluarga Netanyahu sendiri berasal dari Ashkenazi; nama aslinya adalah Mileikowsky, dengan akar dari Polandia.
Ketegangan etnis ini mencerminkan rasisme struktural yang mengakar di Israel, sebagaimana dicatat sejarawan Avi Shlaim dalam bukunya Three Worlds.
Mendistorsi identitas Yahudi Arab
Para leluhur Mizrahi dibawa ke Israel pada awal 1950-an, setelah gerakan Zionis gagal meyakinkan jutaan Yahudi di AS, Inggris, dan Eropa untuk bermigrasi ke sana. Kepemimpinan Zionis kemudian beralih pada apa yang mereka sebut sebagai “Yahudi Arab”.
Namun, dengan dukungan para penasihat akademik, mereka memulai proyek sistematis untuk mencabut identitas Arab para Yahudi ini dan membentuk mereka menjadi “Yahudi Eropa”.
Agar dapat diterima setara dengan Yahudi Eropa, Yahudi Arab dituntut menunjukkan kebencian, rasisme, dan penghinaan terhadap orang Arab—bahkan terhadap identitas mereka sendiri.
Proses ini menciptakan struktur mental yang sangat rapuh, diperparah oleh kondisi sosial-ekonomi yang buruk, karena mereka didorong ke pinggiran geografis dan sosial masyarakat Israel.
Seiring waktu, masalah kesejahteraan dan ekonomi ini tak pernah ditangani secara serius oleh pemerintah.
Sebaliknya, kelompok-kelompok religius masuk ke dalam pemerintahan dan mulai memberi pengaruh besar terhadap generasi muda.
Konflik pun tak lagi sebatas antara Mizrahi dan Ashkenazi, melainkan meluas menjadi konflik antargenerasi.
Satu generasi muda Israel tumbuh dalam sistem pendidikan nasional-religius, bukan dalam sistem demokratis-sekuler.
Sistem pertama melahirkan lulusan yang teokratis, rasis, anti-demokrasi, dan menolak hak asasi serta hak sipil—namun sepenuhnya setia pada mimpi Zionis.
Selama genosida berlangsung, beredar luas foto-foto “swafoto” generasi ini. Ekspresi wajah, bahasa, serta ujaran kebencian dan rasisme mereka mudah dikenali.
Fenomena ini bukanlah sesuatu yang marjinal, melainkan meluas dan menjadi basis kekuatan utama “Negara Yehuda”.
Menurut Pappé, fenomena ini juga disokong oleh lapisan “ilmiah” semu. Di dekat Tembok Barat di Yerusalem—bersebelahan dengan kompleks Al-Haram Al-Sharif dan Masjid Al-Aqsha—berdiri “Institut Pembangunan Bait Suci Ketiga”, yang diklaim sebagai lembaga akademik untuk mempelajari sejarah kuil-kuil kuno, sekaligus membangun model fisik Bait Suci Ketiga.
Di kalangan Zionis religius, gagasan penghancuran Masjid Al-Aqsa semakin menguat—sebuah tindakan yang niscaya akan membakar dunia Islam.
Salah satu ciri utama visi mesianistik ini adalah membangun Bait Suci Ketiga di atas reruntuhan kompleks Al-Haram Al-Sharif, lengkap dengan ruang ibadah, fasilitas, dan halaman-halamannya.
Aspek lain dari visi misioner ini adalah menghidupkan kembali Kerajaan Daud dan Sulaiman.
Kitab suci sendiri tidak memberikan peta geografis yang jelas, namun dalam imajinasi mereka, wilayah kerajaan itu melampaui Palestina historis, mencakup Yordania, Suriah, dan Lebanon sebagai tahap berikutnya.
Saat ini, gagasan tersebut tampak seperti kegilaan—bukan skenario yang realistis atau mungkin terwujud.
Meski Pappé tidak meyakini ekspansi geografis ini dapat berhasil, ia juga tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka tidak akan mencobanya.
Dalam beberapa hal, itulah yang tampak sedang terjadi: perluasan de facto Israel ke Gaza, selatan Lebanon, dan barat daya Suriah hingga mendekati Damaskus, disertai serangan udara yang terus-menerus.
Menurut Pappé, ini adalah perilaku strategis yang tidak rasional dan berorientasi masa depan, yang pada akhirnya justru akan membawa Israel menuju pembusukan dan perpecahan dalam jangka panjang.
Model pusat gravitasi
Pappé menyebut konstruksi ini sebagai model “pusat gravitasi regional”, dengan Yerusalem Yahudi-Zionis sebagai basis kekuatan di Timur Tengah.
Dari titik inilah seluruh kawasan dikelola—melalui para pengikut dan sekutu, sementara pihak-pihak yang dianggap musuh terus-menerus dikenai hukuman.
Dalam kerangka ini, ruang negara tidak lagi dibatasi oleh wilayah Palestina mandat Inggris atau Palestina historis.
Pappé tidak percaya bahwa ambisi ini akan berhenti sampai di sana. Ia menyerukan kepada Barat untuk menyadari perbedaan mendasar antara wacana Israel untuk konsumsi domestik dalam bahasa Ibrani dan narasi yang diproduksi dalam bahasa Inggris.
Menurutnya, jika seseorang mengunjungi pusat-pusat pendidikan mereka, membaca situs-situs resmi, dan meluangkan waktu mempelajari tulisan serta pidato mereka, akan tampak jelas bahwa ambisinya jauh lebih besar—melampaui sekadar kehadiran militer di Lebanon dan Suriah.
Ambisi yang dimaksud adalah pembangunan kembali Israel biblikal kuno, dengan anggapan bahwa sejumlah wilayah—seperti Yordania—merupakan bagian sah dari kerajaan tersebut, baik berdasarkan klaim sejarah maupun kehendak ilahi yang diyakini diberikan kepada bangsa Ibrani.
Gelombang protes terhadap Benjamin Netanyahu memang memperlihatkan retakan internal di Israel. Namun, tidak tampak perbedaan pendapat mendasar terkait praktik genosida itu sendiri.
Yang terjadi justru benturan antara Zionisme religius—yang diwujudkan dalam apa yang disebut Pappé sebagai “Negara Yehuda”—dan “Negara Israel” lama. Retakan internal ini berjalan beriringan dengan proyek perluasan Israel Raya.
Pertanyaannya kemudian: bagaimana kekuatan-kekuatan ini berkontribusi pada perpecahan entitas Israel menjadi “Negara Yehuda” dan “Negara Israel”?
Menurut Pappé, seluruh kebijakan dan strategi tersebut, ketika diterapkan di dunia nyata, terhubung secara dialektis—saling memengaruhi dalam satu kesatuan dinamis.
Ia mengibaratkannya seperti permainan biliar: satu pukulan akan menggerakkan bola-bola lain.
Semakin agresif ekspansi Israel dan semakin brutal langkah-langkah hukumannya di berbagai penjuru dunia Arab, semakin besar pula perubahan internal yang dipaksakan pada dunia Arab—perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Musim Semi Arab” memang tidak menghasilkan perubahan radikal dalam struktur kekuasaan. Namun, eskalasi ekspansi regional Israel dan kebijakan-kebijakan pembalasannya, menurut Pappé, berpotensi melahirkan gelombang revolusi yang berkelanjutan.
Apa yang dimulai pada 2011 sebagai salah satu ekspresi pencarian sistem politik Arab baru, dapat bermuara pada lahirnya rezim, pemimpin, pemerintahan, dan elite politik yang lebih mencerminkan kehendak masyarakat Arab—khususnya dalam isu Palestina.
Dalam kondisi demikian, Israel tidak lagi berhadapan dengan dua kelompok kecil gerilyawan bersenjata—yang meskipun tidak berhasil dikalahkan sepenuhnya—masih dapat dihadapi.
Sebaliknya, Israel akan berhadapan dengan angkatan bersenjata konvensional. Tantangan kedua bersifat ekonomi.
Ekspansi yang dijalankan dengan cara yang, menurut Pappé, “gila” ini—seperti halnya pemerintahan populis di mana pun—akan menuntut harga ekonomi yang sangat mahal.
Jalur-jalur perpecahan
Bagian tersulit dalam buku Pappé adalah merumuskan jalur atau peta jalan konkret menuju perpecahan negara Israel. Ia mengaku tidak kesulitan membayangkan bentuk Palestina historis pada 2048.
Namun, pertanyaan utama bagi para pendukung solusi satu negara demokratis adalah: bagaimana cara mencapainya?
Dalam bagian kedua bukunya, Pappé mencoba menjawab pertanyaan ini dengan pendekatan imajinati.
Berangkat dari pengalaman dan refleksinya sebagai seorang lelaki tua yang menoleh ke belakang untuk memahami apa yang mungkin terjadi, setidaknya dua dekade ke depan.
Ia secara sadar menghindari gambaran romantis tentang dekolonisasi dan kekacauan yang mungkin menyertainya.
Sejarah, tegasnya, tidak pernah mencatat satu pun proses dekolonisasi yang sepenuhnya damai atau mulus.
Karena itu, Pappé memilih bersikap realistis: memasukkan kemungkinan kemunduran dan kekerasan.
Ia juga berharap kekerasan tersebut terbatas dan menjadi pengecualian, bukan norma.
Ia juga menekankan dampak kumulatif dari langkah-langkah dramatis yang dapat diambil berbagai aktor untuk memengaruhi kenyataan di lapangan.
Sebagai contoh, ia meyakini akan terjadi perubahan dalam tubuh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Ia tidak tahu apakah perubahan itu akan melahirkan PLO versi baru atau sebuah gerakan pembebasan yang sepenuhnya baru.
Namun, ia yakin akan muncul suara Palestina yang lebih tegas—yang meninggalkan solusi dua negara dan mampu menghimpun spektrum Palestina seluas mungkin di sekitar satu visi dan program politik.
Program ini, menurutnya, akan memaksa dunia internasional mengakui bahwa inilah posisi resmi Palestina—bukan pandangan kelompok terisolasi atau faksi tertentu, melainkan sikap kolektif gerakan pembebasan Palestina.
Skenario ini akan semakin realistis jika Israel secara ilegal mencaplok Tepi Barat—sesuatu yang, menurut Pappé, sangat mungkin dicoba.
Dalam membaca masa depan, Pappé menolak pendekatan deterministik atau teleologis, terutama terkait kebijakan AS.
Ia memandang sejarah sebagai proses siklikal, bukan garis lurus yang terus bergerak maju. Karena itu, ia meyakini adanya peluang kuat bagi munculnya pola baru yang menjauh dari dominasi kebijakan Amerika.
Pemimpin populis seperti Donald Trump, tulisnya, tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengelola ekonomi, masyarakat, dan hubungan internasional.
Oleh sebab itu, setiap perubahan positif dalam kebijakan AS kemungkinan baru akan terjadi dalam jangka panjang.
Namun, perubahan tersebut akan berperan penting dalam mempersempit pilihan Israel untuk terus mempertahankan apartheid, ekspansi wilayah, pembersihan etnis, dan genosida.
Pappé juga mengingatkan satu hal penting: meskipun dalam konfrontasi terakhir (2023–2025) Israel berhasil memberikan pukulan militer terhadap Hizbullah, serta mempersempit ruang gerak Iran dan Hamas, Israel tetap menduduki jutaan warga Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan di dalam wilayah Israel sendiri—bertentangan dengan kehendak mereka.
Israel juga menghadapi jutaan pengungsi Palestina yang hidup di kamp-kamp di sekitar perbatasannya, yang memiliki keterkaitan dengan milisi lokal dan gerakan perlawanan. Realitas ini, menurut Pappé, tidak akan berubah.
Kondisi tersebut melipatgandakan tekanan militer eksternal terhadap Israel. Ia berharap tekanan ini pada akhirnya memicu dinamika internal—bab terakhir dan paling krusial dalam skenario ini.
Pada tahap ini, masyarakat Yahudi di Israel akan mengalami perubahan mendasar, serupa dengan transformasi komunitas kulit putih di Afrika Selatan, ketika mereka akhirnya menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain bernegosiasi dengan kenyataan.
Mungkin skenario ini tampak tidak realistis saat ini. Namun, Pappé berbicara tentang masa depan yang berbeda, dibentuk oleh rangkaian peristiwa dan tekanan yang terjadi hingga titik itu tercapai. Ia juga yakin akan muncul dua dinamika sosial utama pada fase akhir ini.
Pertama, warga Israel yang tidak ingin hidup dalam negara apartheid—terutama mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda atau peluang kerja yang baik di luar negeri—akan memilih pergi. Fenomena serupa pernah terjadi di kalangan komunitas kulit putih Afrika Selatan.
Kedua, seiring dimulainya proses kembalinya warga Palestina dari pengungsian dan diaspora, perubahan demografi dan pilihan politik akan terjadi. Ini mungkin mengejutkan sebagian pihak.
Namun, berdasarkan pengalamannya selama 70 tahun berinteraksi dengan masyarakat Palestina, Pappé menyatakan keyakinannya.
Yaitu orongan utama rakyat Palestina ketika mendekati momen pembebasan dari penindasan, kolonialisme, dan pembersihan etnis bukanlah balas dendam, melainkan pemulihan—kompensasi, dan pembangunan kembali kehidupan normal yang pernah mereka miliki sebelum kedatangan Zionisme.
Model inspiratif bagi masa depan itu, tegas Pappé, tidak akan datang dari pola-pola politik Eropa modern.
Ia justru merujuk pada periode sebelum 1948, ketika Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara nyata—bukan hanya di Palestina historis, tetapi juga di kawasan Mediterania Timur dan Afrika Utara.
Keletihan militer: Manusia dan persenjataan
Militer Israel kini berada di bawah tekanan berat dan harus beroperasi dalam kondisi yang semakin menyesakkan.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa sejumlah besar tentara cadangan tidak kembali ke unit mereka dan tidak ikut serta dalam perang di Gaza. Tingkat korban pun disebut jauh lebih tinggi dibandingkan angka resmi yang diumumkan.
Sejumlah estimasi bahkan menyebutkan bahwa sejak Oktober 2023, jumlah warga Israel yang meninggalkan negara itu mencapai angka ratusan ribu—dalam beberapa perkiraan, hingga setengah juta orang.
Tampak jelas adanya gejala keletihan struktural. Sejak awal, militer Israel tidak pernah dirancang untuk menghadapi perang berkepanjangan yang bersifat menguras tenaga. Israel adalah negara kecil, dengan populasi sekitar tujuh juta jiwa.
Karena itu, tekanan militer yang berlangsung lama, ditambah tekanan internal, niscaya akan memberi dampak signifikan dan berkontribusi pada skenario perpecahan dan perubahan.
Pappé memandang keletihan ini sebagai indikator tambahan bagi kemungkinan disintegrasi. Ia membedakan dua jenis keletihan utama.
Pertama, keletihan manusia yang akut. Tentara cadangan, dalam praktiknya, telah berubah menjadi tentara reguler.
Sejak 2023, mereka bertugas dalam durasi yang sangat panjang—nyaris setara dengan hari dinas tentara aktif.
Para personel cadangan bukan hanya terkuras secara fisik dan mental akibat keterlibatan militer yang terus-menerus, tetapi juga kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Dampaknya merembet ke kehidupan keluarga dan stabilitas sosial mereka.
Kedua, keletihan yang berkaitan dengan konsumsi dan degradasi perlengkapan militer. Seperti diungkapkan harian Haaretz baru-baru ini, Israel menghadapi persoalan serius terkait peralatan militernya.
Strategi produksi dan pengadaan alutsista Israel sejak lama didasarkan pada asumsi bahwa perang dapat dimenangkan dengan memenuhi tiga prasyarat utama.
Pertama, Israel harus menjadi pihak yang memulai perang—sesuatu yang tidak terjadi pada 2023.
Kedua, perang harus berlangsung di wilayah musuh—yang juga tidak selalu terjadi.
Ketiga, dan yang paling krusial, perang harus berlangsung sangat singkat. Jika tidak, konflik akan berubah menjadi perang pengurasan.
Ketiga prasyarat tersebut tidak terpenuhi. Akibatnya, kualitas perlengkapan militer mengalami penurunan, begitu pula kemampuannya untuk melayani tujuan-tujuan politik pemerintah.
Pappé menegaskan, Israel masih memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Tidak ada ilusi bahwa tentara Israel dapat dikalahkan dalam waktu dekat—kondisi itu, katanya, belum tercapai.
Namun, keletihan ini juga mencerminkan rapuhnya kohesi sosial antara mereka yang menjalani wajib militer dan mereka yang tidak.
Dalam situasi seperti ini, pilihan yang paling menarik bagi warga Israel yang tidak ingin anak-anak mereka terus-menerus diseret ke medan perang adalah meninggalkan Israel. Fenomena ini terjadi dalam jumlah yang tidak kecil.
Hal itu tidak berarti bahwa tidak ada kaum muda Israel yang tetap bersemangat untuk mendaftar—bahkan bergabung dengan unit-unit elite.
Militer Israel masih memiliki kapasitas besar untuk menindas warga sipil Palestina, menghancurkan kehidupan mereka, melakukan pembunuhan massal, dan menebar teror—sebagaimana yang berlangsung di Tepi Barat dan di dalam wilayah Israel sendiri.
Pertanyaan mendasarnya, jika merujuk pada pelajaran sejarah, adalah: apakah situasi semacam ini dapat terus berlangsung tanpa batas?
Jawaban sejarah bersifat tegas: tidak. Selalu ada batas bagi perilaku negara yang menyimpang dari norma.
Ada batas bagi praktik mempertahankan jutaan manusia selama puluhan tahun di bawah pemerintahan militer yang dipaksakan.
Terlebih di sebuah kawasan di mana para penjajah merupakan minoritas pendatang, berhadapan dengan mayoritas penduduk yang mengakar, meski keseimbangan kekuatan masih memungkinkan dominasi mereka bertahan.
Namun, Pappé menegaskan, kondisi ini tidak akan berlanjut—baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.