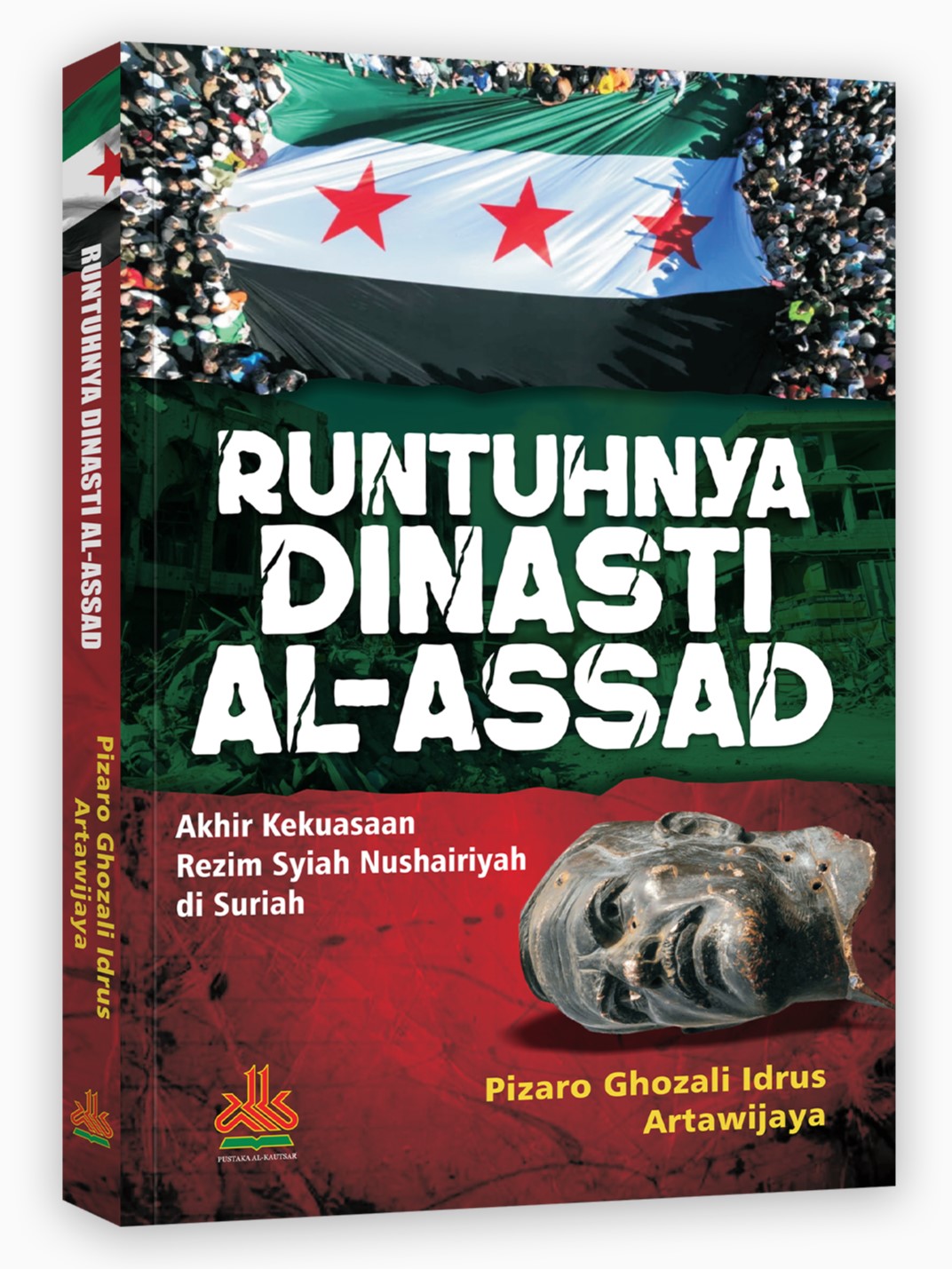Oleh: Jasim Al-Azzawi
Ada kalanya sejarah bangkit dari tidur panjangnya dan menjatuhkan vonis dengan kejernihan sekeras palu yang menghantam besi. Dikeluarkannya Tony Blair dari rencana dewan perdamaian Gaza adalah salah satu momen itu—tegas, tak terbantahkan, nyaris bersifat penghakiman.
Seorang tokoh yang pernah melangkah di panggung dunia dengan keyakinan seorang “pembebas” kini mendapati dirinya ditolak dari kawasan yang ikut ia porak-porandakan. Bagi negara-negara Arab dan Muslim, nama Blair bukan identik dengan diplomasi atau kenegarawanan. Nama itu adalah sinonim dari bencana.
Tak ada perdamaian bagi penjahat perang
Upaya Blair untuk duduk di meja rekonstruksi Gaza runtuh oleh beban warisan yang tak bisa ia tinggalkan atau poles ulang. Dukungan penuhnya terhadap invasi Irak tahun 2003—perang yang dibenarkan melalui dokumen intelijen yang dimanipulasi dan ketakutan apokaliptik—meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Pasukan bergerak, bom dijatuhkan, dan sebuah bangsa dicabik-cabik atas nama “pembebasan”.
Bagi dunia Arab, citra Blair berdiri berdampingan dengan George W. Bush adalah simbol abadi dari penipuan. Ia tidak dilupakan. Ia tidak dimaafkan.
Penolakan dari negara-negara Arab dan Muslim disampaikan dengan keserempakan yang jarang terjadi. Pesannya lugas: arsitek kehancuran Irak tak bisa menyamar sebagai penyembuh Gaza.
Tekanan itu begitu kuat hingga Donald Trump—yang semula memuji Blair sebagai “orang yang sangat baik”—akhirnya menarik diri secara senyap. Bahkan Trump memahami bahwa ia tak bisa menunjuk seorang mediator yang wajahnya membangkitkan memori kolektif tentang invasi, pendudukan, dan hancurnya sebuah kawasan. Blair dinilai “tidak dapat diterima oleh semua pihak”, sebuah eufemisme diplomatik untuk penyingkiran.
Para pendukung Blair mengangkat perannya dalam proses perdamaian Irlandia Utara sebagai bukti kapasitasnya. Namun argumen itu rapuh dan cepat runtuh ketika dihadapkan pada rekam jejaknya sebagai utusan Kuartet Timur Tengah—delapan tahun panjang tanpa capaian berarti.
Para pengkritik mengingat seorang diplomat yang lebih nyaman berpidato ketimbang memecah kebuntuan, seorang tokoh yang memperkaya portofolionya dengan konsultasi korporasi dan peran penasihat di negara-negara Teluk, sementara Gaza tercekik oleh blokade.
Bahkan di koridor Brussels dan New York, masa jabatan Blair kerap dibicarakan dengan rasa canggung—kegagalan yang enggan diakui secara terbuka. Jika inilah riwayat yang diharapkan mengantarnya ke dewan perdamaian Gaza, maka itu terbukti kosong.
Bayang-bayang Kissinger
Penyingkiran Blair bukan semata kalkulasi politik, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral. Ia menanggung kutukan yang sama seperti Henry Kissinger—tokoh yang dielu-elukan di Washington namun dicela hampir di seluruh belahan dunia lain.
Kissinger menerima Hadiah Nobel Perdamaian dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih ternodai abu desa-desa Kamboja yang dibombardir. Ia berkeliaran di pusat kekuasaan, namun tak pernah lepas dari bayang-bayang kejahatan perang. Di Global Selatan, kehadirannya memicu amarah, bukan penghormatan.
Jejak Blair mengikuti alur tragis yang serupa. Seperti Kissinger, ia mencoba menata ulang citra sebagai penasehat tatanan internasional, seolah-olah puing-puing Baghdad dan Fallujah akan menghilang dengan sendirinya. Ia berbicara tentang demokrasi dan stabilitas, namun salah membaca suasana. Dunia Arab tidak melupakan siapa yang menyalakan api.
Winston Churchill dan pola yang berulang
Kecaman terhadap Blair juga bukan tanpa preseden. Winston Churchill—diagungkan di Eropa karena perlawanan terhadap Hitler—memiliki reputasi lain di dunia bekas jajahan: tokoh yang membiarkan kelaparan Bengal, menumpas pemberontakan dengan kekerasan, dan memandang bangsa-bangsa jajahan sebagai kaum barbar yang tak layak menentukan nasib sendiri.
Churchill berusaha tampil sebagai negarawan global pascaperang, tetapi di India, Kenya, dan Timur Tengah, ia dikenang sebagai pengawas imperium yang menilai nyawa manusia berdasarkan hierarki rasial.
Polanya jelas: mereka yang menyalakan api dengan keyakinan kejam tak bisa kemudian berpose sebagai pemadam kebakaran. Sejarah tidak lupa, dan darah yang tertumpah mengikuti mereka ke setiap ruang, setiap dewan, setiap permohonan akan relevansi.
Blair pun mengalami kenyataan pahit bahwa reputasi terbelah oleh geografi. Di London, ia diperdebatkan. Di Washington, ia diterima. Di Timur Tengah, ia dicurigai, ditolak, atau dibenci. Upayanya membungkus diri sebagai wali rekonstruksi Gaza adalah ilusi—yang segera dipatahkan oleh negara-negara Arab dan Muslim.
Dengan menyingkirkan Blair, pemerintahan Trump mungkin membuka jalan bagi Jared Kushner dan pengusaha properti Steve Witkoff—figur dengan kontroversinya sendiri, namun tanpa warisan toksik khas Blair.
Meski demikian, laporan menyebut Blair masih mungkin berperan di balik layar, memberi masukan periferal. Namun pesannya tegas: ia tidak akan berada di pusat. Ia bukan mediator, bukan penyelamat, bukan arsitek masa depan Gaza. Masanya telah lewat. Namanya terlalu sarat darah.
Penyingkiran Blair mencerminkan sesuatu yang lebih besar: ingatan kolektif kawasan ini terhadap Perang Irak. Kuburan massal, kota-kota yang tercabik, bangkitnya milisi sektarian, lahirnya ISIS—semua itu bukan abstraksi, melainkan pengalaman hidup. Ketika Blair mencoba memasuki ruang perdamaian, kenangan-kenangan itu berdiri sebagai penjaga, memaksanya berbalik arah.
Pada akhirnya, kejatuhan Blair bukan catatan kaki dalam kisah Gaza. Ia adalah penegasan atas kebenaran yang dipahami kawasan ini dengan pahit: para penyulut perang jarang menjadi pendamai yang kredibel. Mereka membawa asap ke mana pun melangkah. Mereka menyeret bayang-bayang ke setiap perundingan. Mereka memanggil hantu ke setiap ruangan.
Blair mencari peran. Yang ia temukan justru putusan: pergi. Sejarah tidak pernah lupa.
Jasim Al-Azzawi bekerja untuk beberapa organisasi media, termasuk MBC, Abu Dhabi TV, dan Aljazeera English sebagai pembawa berita, presenter program, dan Produser Eksekutif. Ia meliput konflik-konflik penting, mewawancarai para pemimpin dunia, dan mengajar kursus media.